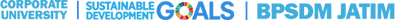Netralitas Dalam ANOMALI Birokrasi - Ramliyanto, SP., MP
 Birokrasi dalam perspektif Max Weber adalah perangkat administrasi yang berorientasi pada tujuan, yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip rasional untuk mencapai tujuan secara efektif. Konstruksi teori Weber tentang birokrasi diturunkan dari gagasannya tentang 3 (tiga) jenis legitimasi kewenangan (authority), yang terdiri dari; otoritas tradisonal (karena tradisi), otoritas karismatik (karena karisma personalitas), dan otoritas legal – rasional (karena aturan-aturan legal yang rasional). Bentuk otoritas yang terakhir tersebut merupakan dasar bagi terbentuknya apa yang disebut birokrasi : legal-rational authority forms the basis of bureaucracy. Desain birokrasi Weberian ini mengarah pada apa yang disebut Max Weber dengan tipe ideal birokrasi. Dengan karakteristik yang meliputi; 1) staf menjalankan tugas impersonal dari jabatan mereka, 2) hierarki jabatan yang jelas, 3) ketegasan fungsi jabatan, 4) pejabat diangkat berdasar kontrak, 5) dipilih berdasarkan kualifikasi personal, 6) memiliki gaji dan hak pensiun, 7) pos jabatan adalah lapangan kerja pokoknya, 8) terdapat struktur karir dan promosi, 9) kemungkinan adanya pejabat yang tidak sesuai baik dengan posnya, dan 10) tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam.
Birokrasi dalam perspektif Max Weber adalah perangkat administrasi yang berorientasi pada tujuan, yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip rasional untuk mencapai tujuan secara efektif. Konstruksi teori Weber tentang birokrasi diturunkan dari gagasannya tentang 3 (tiga) jenis legitimasi kewenangan (authority), yang terdiri dari; otoritas tradisonal (karena tradisi), otoritas karismatik (karena karisma personalitas), dan otoritas legal – rasional (karena aturan-aturan legal yang rasional). Bentuk otoritas yang terakhir tersebut merupakan dasar bagi terbentuknya apa yang disebut birokrasi : legal-rational authority forms the basis of bureaucracy. Desain birokrasi Weberian ini mengarah pada apa yang disebut Max Weber dengan tipe ideal birokrasi. Dengan karakteristik yang meliputi; 1) staf menjalankan tugas impersonal dari jabatan mereka, 2) hierarki jabatan yang jelas, 3) ketegasan fungsi jabatan, 4) pejabat diangkat berdasar kontrak, 5) dipilih berdasarkan kualifikasi personal, 6) memiliki gaji dan hak pensiun, 7) pos jabatan adalah lapangan kerja pokoknya, 8) terdapat struktur karir dan promosi, 9) kemungkinan adanya pejabat yang tidak sesuai baik dengan posnya, dan 10) tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam.
Betapapun konstruksi Weber tersebut banyak memunculkan kritik dan perdebatan sampai sekarang (Sebagai peng-awal, Karl Marx misalnya - yang menyebutkan bahwa birokrasi bukan sekedar mesin pelaksana administratif kebijakan-kebijakan politik, namun justru merupakan aktor yang secara aktif ikut mengendalikan warna dari politik itu sendiri), namun cukup mudah bagi kita untuk menyimpulkan bahwa birokrasi merupakan institusi pelaksana pelayanan publik dengan fungsi-fungsi tertentu yang diangkat berdasarkan kualifikasi profesionalitas, terikat pada mekanisme internal tertentu, serta independen dari kepentingan-kepentingan di luar organisasinya.
Anomali Birokrasi
Dalam perjalanannya tentu saja wajah “indigeneous” birokrasi telah mengalami banyak anomali jika tak bisa dikatakan alienasi, khususnya yang terkait dengan kontestasinya dalam politik. Kalangan Weberian, betapapun tidak secara diametral mendikotomi birokrasi dan politik, nampaknya sepakat bahwa birokrasi seharusnya steril dari kepentingan politik.
Namun demikian realitas tidak bisa dipungkiri, bahwa birokrasi tidak bisa sepenuhnya steril, sebagaimana ditegaskan oleh Mohtar Mas’oed (2003) yang menyebutkan bahwa “birokrasi tidak pernah bergerak dalam ‘ruang hampa politik’ dan bukan aktor netral dalam politik”. Fenomena ini tentu saja bukan khas birokrasi Indonesia, tetapi banyak melanda negara-negara khususnya pasca kolonialisme, dimana birokrasi seringkali mengidentifikasikan dirinya sebagai sebuah kekuatan dominan dalam membuat kebijakan-kebijakan publik. Untuk kasus birokrasi Indonesia pada era orde baru, Karl D. Jackson (1978) dalam ‘Bureaucratic Polity: A Theoritical Framework for The Analysis of Power and Communication in Indonesia’ mengkonsepsikan kekuasaan dan partisipasi pembuatan keputusan politik di Indonesia ada di tangan birokrat sipil dan militer tingkat tinggi didukung oleh kaum teknokrasi. Model tersebut digunakan sebagai kerangka oleh Harold Crouch untuk menjelaskan karakter bureaucratic polity di Indonesia. Menurutnya, bureaucratic polity memiliki karakteristik tersendiri yang bercirikan; 1) lembaga politik yang paling dominan adalah birokrasi, 2) lembaga politik lainnya (parlemen, parpol, dan kelompok kepentingan) lemah, sehingga tidak mampu mengontrol birokrasi, dan 3) massa di luar birokrasi lemah secara politik dan ekonomi.
Tanpa bermaksud menyetujui ataupun menentang pandangan-pandangan tentang birokrasi di Indonesia di masa orde baru maupun saat ini, nampaknya berbagai fenomena empirik yang dapat dibaca awam sekalipun dapat membuktikan bahwa birokrasi Indonesia tidak bisa sepenuhnya menghindar dari keberpihakan terhadap politik. Namun yang harus diingat adalah bahwa ”keberpihakan” birokrasi bukanlah keberpihakan teknis-mekanis terhadap kepentingan politik tertentu yang sampai mengabaikan fungsinya dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, tetapi sebuah ”keberpihakan” sistematis yang prosedural. Salah satu contoh konkrit adalah dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional bahwa salah satu pendekatan dalam pembangunan adalah pendekatan politik, selain pendekatan teknokratik, partisipatoris dan bottom-up/top-own. Dalam penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dari keterangan ini sangat jelas seperti apa bentuk ”keberpihakan” birokrasi dalam kontestasi politik di Indonesia, yang sama sekali bukan keberpihakan dalam rangka membantu atau turut serta dalam memenangkan suatu kepentingan atau kelompok politik tertentu.
Netralitas Birokrasi
Pertanyaan yang sering muncul dalam kaitannya birokrasi dengan politik adalah, mengapa netralitas birokrasi sering menjadi perdebatan ? dengan kata lain, mengapa netralitas birokrasi menjadi penting dalam momentum-momentum politik seperti pemilihan uimum atau pemilihan kepala daerah.
Pentingnya netralitas birokrasi dalam kontestasi politik bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif kewenangan dan fungsi, bahwa dalam birokrasi terinternalisasi berbagai kewenangan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ketidaknetralan birokrasi dapat dipastikan akan menjerumuskannya ke dalam keberpihakan terhadap kepentingan tertentu yang kemudian akan bermuara pada penyalahgunaan kewenangan. Tentu mudah dibayangkan dampak buruk yang diakibatkan jika birokrasi menggunakan kewenangannya untuk kepentingan kelompok politik tertentu, baik dampak terhadap kinerja birokrasi itu sendiri maupun dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Kedua, dari perspektif anggaran dan fasilitas, bahwa birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibekali dengan anggaran dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Jika birokrasi tidak netral, lalu anggaran dan fasilitas yang tersedia digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, tentu saja berbagai dampak negatif akan ditimbulkan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terhambatnya pembangunan dan buruknya pelayanan masyarakat.
Terkait dengan birokrasi sebagai sebuah lembaga yang terdiri dari pegawai negeri, aturan tentang netralitas birokrasi telah dijelaskan secara tegas dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara lebih teknis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/08/M.PAN/2005. Ada dua hal penting dari Surat Edaran ini disamping larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi unsur dalam kepanitiaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah seperti Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS. Pertama, larangan bagi pegawai negeri menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye. Kedua, larangan membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (dalam Pemilihan Presiden atau Pemilihan Kepala Daerah) selama masa kampanye.
Klausul dalam undang-undang maupun surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dimaksud tentu saja tidak bisa menimbulkan efek apa-apa terutama terhadap pegawai negeri yang terbukti tidak netral, jika tidak disertai dengan instrumentasi pengawasan dan penindakannya. Oleh sebab itu menjadi amat penting dan mendesak agar netralitas birokrasi tidak sekedar menjadi himbauan, atau mengandalkan munculnya kesadaran pribadi aparat birokrasi terhadap pentingnya sikap netral, tetapi pengawasan serta penindakan sesuai koridor peraturan perundangan jika terbukti akan menjadi faktor pengungkit bagi tumbuhnya sebuah birokrasi yang bersih dan berwibawa.
*) Penulis adalah PNS Pada Badan DIKLAT Provinsi Jawa Timur
Berita Lain
Copyright by BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR. All Rights Reserved